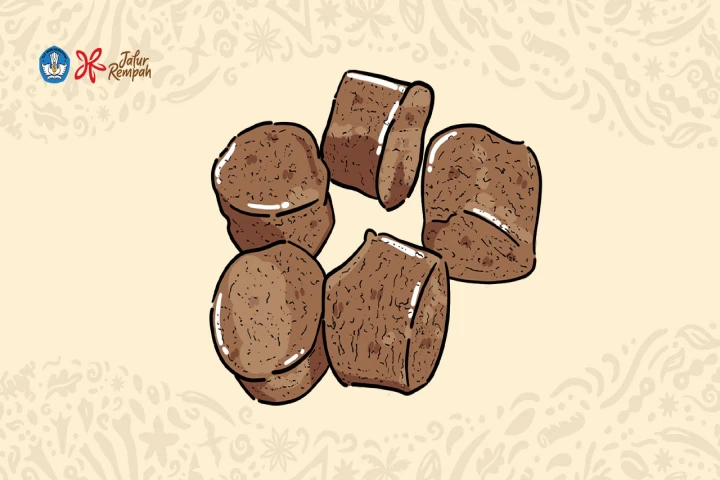Pada masa kolonial Belanda, kelas masyarakat dibagi tiga, kelompok kulit putih (barat), kedua kelompok Timur Asing (khususnya orang China, India, dan Arab), kelompok Indo-Eropa atau anak-anak yang lahir dari perkawinan silang antara pribumi, serta China dengan orang-orang Eropa. Kelas terakhir ditempati oleh masyarakat asli pribumi yang kebanyakan berasal dari pedalaman (Mestika Zed, 2009: 10). Hal ini sesuai dengan diberlakukannya pasal 131 Indische Staatsregeling (IS) dan pasal 163 IS di mana dalam pasal tersebut penduduk Hindia Belanda dibagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan Eropa, Golongan Bumiputera, dan Golongan Timur Asing.
Pertumbuhan awal Kota Padang tercipta berkat interaksi perdagangan yang melibatkan antaretnis, yaitu antara pemerintah kolonial termasuk para pedagang Eropa dengan pedagang pendatang, seperti China, Arab, dan India, orang Nias, dan orang Minangkabau. Orang Nias, Aceh, Arab, dan India diperkirakan sudah ada sebelum kedatangan orang Belanda. Kota Padang di abad XVII cukup sederhana karena aktivitas niaga hanya berlangsung di pelabuhan kecil sekitar Pasar Gadang, sedangkan di kedua sisi Batang Arau terdapat pemukiman penduduk. Imigran pertama yang datang ke Padang membuka pemukiman di tepi selatan Arau, yang selanjutnya dikenal sebagai wilayah Seberang Padang dan bergerak ke arah utara sehingga terbentuk kampung-kampung Alang Lawas, Ranah, Olo, Parak Gadang, dan Ganting. Kampung-kampung ini telah ada jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa terutama Belanda.
Alang Lawas dan Ganting dikenal dengan Nan VIII Suku yang merupakan konfederasi 8 suku dan dikepalai oleh seorang penghulu. Mereka kebanyakan berprofesi sebagai pedagang dan memiliki tempat peribadatan, tanah kuburan, dan pimpinan (Lindayanti, 2020: 1). Aktivitas perdagangan terjadi di sekitar sekitar benteng (kantor dagang) VOC. Benteng ini terletak di kaki Gunung Padang sebelah tepi utara Batang Arau. Selain itu, aktivitas perdagangan juga berlangsung di pasar-pasar pribumi, yaitu Pasar Gadang. Sampai saat ini, aktivitas perdagangan di Pasar Gadang masih berjalan meskipun tidak semasif dulu.
Orang India di Kota Padang mulai terlihat sekitar abad IX Masehi, yaitu kelompok gilde (mirip dengan perusahaan firma ala Eropa abad Renaisans), dan sudah beroperasi di sekitar Pantai Barat Sumatra, termasuk di Pariaman dan Padang. Persamaan agama Islam membuat orang-orang India ini cepat terintegrasi ke dalam unsur pribumi. Eksistensi mereka di Padang sudah sejak lama ditandai dengan adanya Kampung Keling dan sebuah Masjid Keling yang sudah didirikan sejak masa pemerintahan Inggris di Padang. Gelombang kedua kedatangan orang-orang India, yaitu orang Keling atau Tamil dari daerah Coromandel, India Selatan. Kebanyakan orang India Keling merupakan pedagang rempah-rempah dan kain dari negeri asalnya meskipun jumlah mereka tidak banyak. (Mestika Zed, 2009: 10-11).
Keragaman budaya lainnya terlihat dari budaya serak gulo yang dilakukan oleh warga keturunan India yang berada di Kota Padang. Budaya itu biasa dilaksanakan bertepatan dengan 1 Jumadil Akhir 1441 Hijriah untuk mengenang Maulud Syekh Sahul Hamid. Perayaan tersebut disambut meriah oleh masyarakat keturunan India dan masyarakat asli. Beberapa ton gula dipersiapkan untuk acara ini. Uniknya, gula ini didapatkan dari hasil sumbangan masyarakat asli dengan keturunan India. Hal itu menggambarkan harmonisasi hubungan antara kedua masyarakat. Pada acara tersebut, peserta tidak dibatasi dan boleh diikuti siapa saja. Tradisi tersebut dilaksanakan di Masjid Muhammadan, yaitu rumah ibadah yang dibangun oleh India Muslim, terdiri dari tiga lantai bercorak arsitektur India. Hingga kini, masjid itu tetap eksis. Unsur India pada masjid dapat dilihat dari bagian depan masjid, kaca jendela, dan langit-langit. Setelah diamati saksama, masjid tersebut menyuguhkan ornamen dan gaya hiasan India yang khas (BPCB Sumbar, 2019: 1).
_________
Sumber Referensi
Zed, Mestika. (2009). Kota Padang Tempo Doeloe (Zaman Kolonial). Universitas Negeri Padang: Pusat Kajian Sosial Budaya dan Ekonomi.
Lindayanti. (2020). “Interaksi Antaretnis di Kota Padang pada Masa Kolonial” dalam Seminar “Sehari Padang Lama dalam Perspektif Sejarah dan Masa Depan”.
https://deddyarsyablog.wordpress.com/2014/02/14/benteng-voc-di-muara-padang
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbsumbar/pesona-budaya-masjid-muhammadan/
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/17030/05.2%20bab%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://deddyarsyablog.wordpress.com/2014/02/14/benteng-voc-di-muara-padang).
https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/17030/05.2%20bab%202.pdf?sequence=2&isAllowed=y
_________
Ditulis oleh Merry Kurnia, merrykurnia86@gmail.com
Editor: Dian Andika Windah & Tiya S.
Sumber gambar: Zhilal Darma/Wikipedia